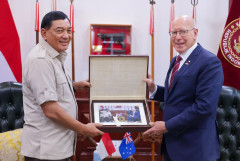Realitas Kehidupan Sekolah di Korut: Gaji Guru Dibebankan ke Siswa

Oleh Bella Seo*
Korea Utara (Korut) baru-baru ini, telah mempromosikan penerapan Undang-Undang Pengasuhan Anak (2022) sebagai "contoh model perlindungan hak asasi manusia" di komunitas internasional. Dalam surat kabar milik pemerintah Rodong Sinmun menyatakan, "Tunjangan pengasuhan anak tersedia bahkan di daerah pegunungan terpencil," sambil mengiklankan bahwa Korea Utara menghormati hak asasi manusia (HAM) anak-anak.
Namun, untuk benar-benar memahami situasi HAM di Korut, kita harus memperhatikan pelanggaran hak asasi manusia yang tersembunyi di balik propaganda yang menyimpang tersebut. Saya lahir di Korut dan tinggal di sana selama 15 tahun sebelum membelot dan menetap di Korea Selatan (Korsel), tempat saya sekarang telah tinggal selama sembilan tahun. Saya ingin berbagi tentang pelanggaran HAM sehari-hari yang saya alami selama masa kuliah.
Selama masa sekolah, rumah dan sekolah saya adalah seluruh dunia saya. Dunia yang luas namun sempit itu menyiksaku setiap hari, seperti bunyi alarm yang disetel setiap 10 menit, terus-menerus mengingatkanku akan ketidakberdayaanku. Di Korut, sekolah membebankan semua biaya pengelolaan, seperti biaya pemeliharaan, perawatan fasilitas, dan gaji guru, kepada siswa.
Jika siswa tidak mampu membayar biaya tersebut, mereka menghadapi hukuman fisik atau perundungan di kelas. Guru secara paksa memungut biaya tersebut dari siswa, dan mereka yang tidak mampu membayar mengalami rasa malu yang luar biasa. Pada akhirnya, semua beban ini jatuh pada orang tua, dan jika mereka tidak mampu menanggung biaya tersebut, siswa tidak dapat menanggung penghinaan dan tekanan dan memilih untuk putus sekolah.
Di sekolah-sekolah Korut, kekerasan dan hukuman fisik adalah hal yang rutin. Jika seorang siswa tidak mampu membayar, guru tanpa pandang bulu memukul siswa tersebut dengan tongkat, memukul tangan, pantat, paha, dan betis mereka. Tindakan kekerasan ini menimbulkan trauma fisik dan psikologis pada siswa muda, yang merupakan pelecehan anak.
Namun, masalahnya adalah di Korut, tidak ada pengakuan atas pelecehan anak, dan kekerasan terhadap anak-anak diterima sebagai bagian alami dari kehidupan. Siswa Korut menghabiskan lebih banyak waktu memegang sekop dan beliung daripada belajar. Selama jam belajar, mereka dipaksa bekerja. Baik itu pemulihan bencana, mobilisasi untuk bertani, atau mengumpulkan besi tua, siswa dikerahkan untuk berbagai jenis kerja paksa.
Saya dicuci otak oleh pendidikan ideologis yang berulang-ulang di Korut dan tidak mempertanyakan mobilisasi paksa, menganggapnya sebagai bagian alami dari kehidupan. Namun, setelah datang ke Korsel, saya menyadari bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat bagi siswa untuk menerima pendidikan, dan bahwa mobilisasi paksa Korut merampas kesempatan dan hak akademis siswa, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Lebih dari 70 tahun telah berlalu sejak pemisahan Korsel dan Korut. Sementara Korsel telah berkembang pesat, Korut masih terjebak di masa lalu. Di dunia di mana kecerdasan buatan (AI) menggantikan tenaga kerja manusia, Korut masih memblokir akses ke internet dan terisolasi dari dunia luar, membuat rakyatnya hidup di tahun 1950-an.
Tidak ada kebebasan bergerak, dan bahkan di Korut, orang tidak dapat bepergian dengan bebas. Mereka yang mengkritik Kim Jong-un dikirim ke kamp penjara politik atau dieksekusi, dan keluarga mereka menghadapi pembalasan. Siswa muda yang ingin belajar terpaksa putus sekolah karena kekurangan uang, dan mereka menjadi sasaran kerja paksa.
Dengan cara ini, Korut tanpa memperhatikan hak asasi manusia, terus menipu dunia dengan mempromosikan hak asasi manusia di panggung internasional. Saya sangat mendesak masyarakat internasional untuk terus memperhatikan, sehingga siswa Korea Utara dapat belajar dengan bebas tanpa kekhawatiran lainnya.
* Penulis adalah pembelot dari Korut dan mahasiswa di Korsel


 Pertahanan - 01 Nov 2025
Pertahanan - 01 Nov 2025